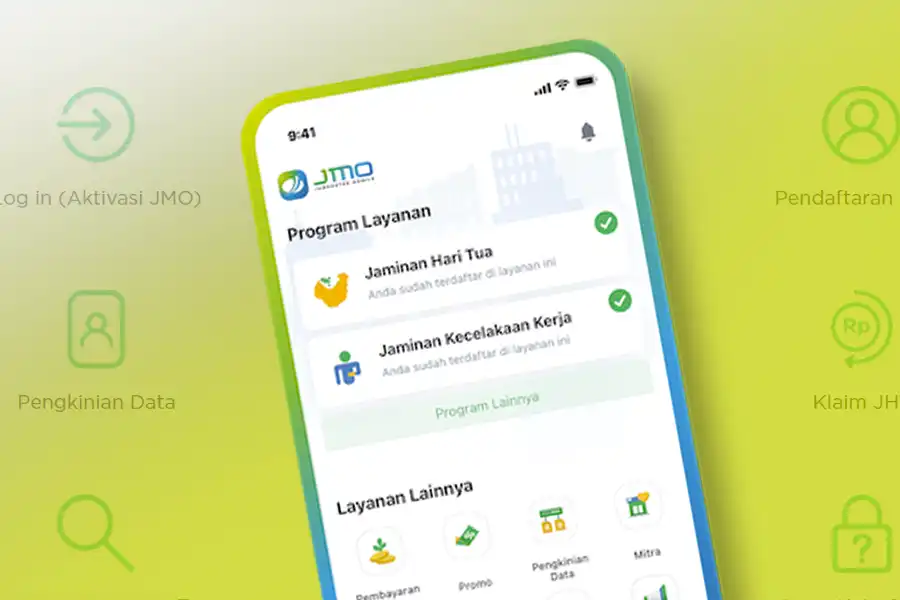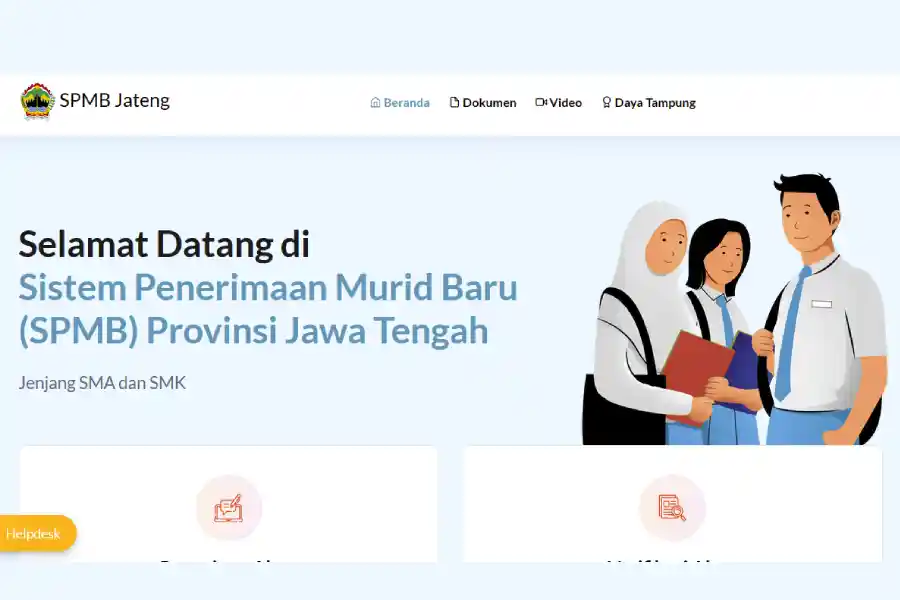Surabaya (pilar.id) – Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman penjara 4,5 tahun kepada mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan.
Vonis tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dalam pemberian izin impor gula yang disebut merugikan negara hingga Rp 578,1 miliar.
Padahal, selama 23 kali persidangan, tidak satu pun bukti yang menunjukkan bahwa Tom Lembong memperoleh keuntungan pribadi dari kebijakan impor tersebut.
Dalam amar putusannya, Lembong dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dari Diskresi Menjadi Vonis
Dalam pledoinya, Tom menegaskan bahwa keputusannya murni merupakan bagian dari diskresi kebijakan, tanpa adanya mens rea (niat jahat). Dalam doktrin hukum pidana, mens rea merupakan unsur krusial untuk membuktikan tindak pidana. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana seharusnya diperdebatkan lebih lanjut.
 Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) Riza Alifianto Kurniawan SH MTCP,
Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) Riza Alifianto Kurniawan SH MTCP,Pakar Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR), Dr. Riza Alifianto Kurniawan, SH, MTCP, menyatakan bahwa kasus ini menyentuh area sensitif antara batas tindakan administratif dan tindak pidana korupsi.
“Ini bisa dilihat sebagai bentuk kriminalisasi kebijakan publik. Padahal, pejabat memiliki ruang diskresi tertentu, terlebih jika tidak terbukti adanya keuntungan pribadi,” ujarnya.
Ratio Hakim Dinilai Ganjil
Majelis Hakim menyatakan bahwa Lembong bersalah karena mengabaikan prosedur koordinasi lintas sektor, yang dianggap memenuhi unsur delik tindak pidana korupsi.
Namun, Riza menilai bahwa penyalahgunaan wewenang dalam konteks pidana harus dibuktikan dengan jelas melalui niat jahat dan perbuatan melawan hukum secara aktif.
“Selama kebijakan tersebut tidak digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan tidak ada perbuatan yang secara aktif melanggar hukum, maka seharusnya hal itu masuk ranah administratif, bukan pidana,” tegasnya.
Kriminalisasi Kebijakan Publik?
Riza juga mengkritisi pendekatan hakim dalam menafsirkan unsur “melawan hukum” dalam konteks administratif. Menurutnya, hal ini membuka celah ambiguitas hukum yang dapat mengancam independensi pengambilan keputusan di tubuh lembaga eksekutif.
“Yang terjadi adalah kegagalan meyakinkan hakim bahwa tidak ada niat jahat. Namun, tafsir tersebut sangat layak diperdebatkan, karena menyentuh prinsip dasar dalam hukum pidana,” katanya.
Putusan ini juga dinilai bertentangan dengan prinsip Business Judgement Rule (BJR), yang selama ini menjadi pijakan dalam tata kelola pemerintahan dan korporasi modern. Jika tafsir hukum terus bergerak ke arah kriminalisasi kebijakan, maka akan muncul efek jera bagi pejabat dalam mengambil keputusan berani—meskipun demi kepentingan publik. (rio/hdl)

 2 months ago
74
2 months ago
74